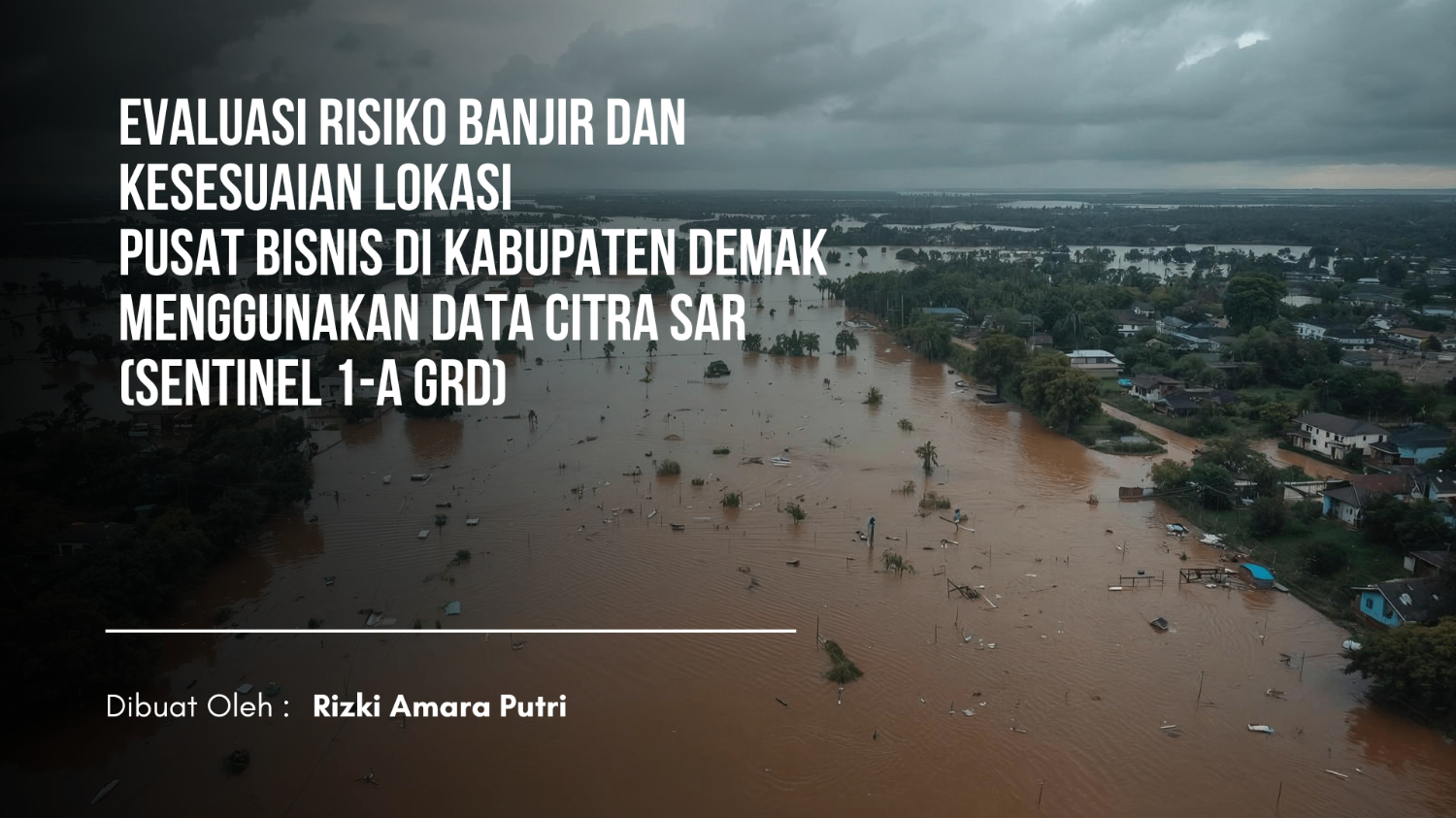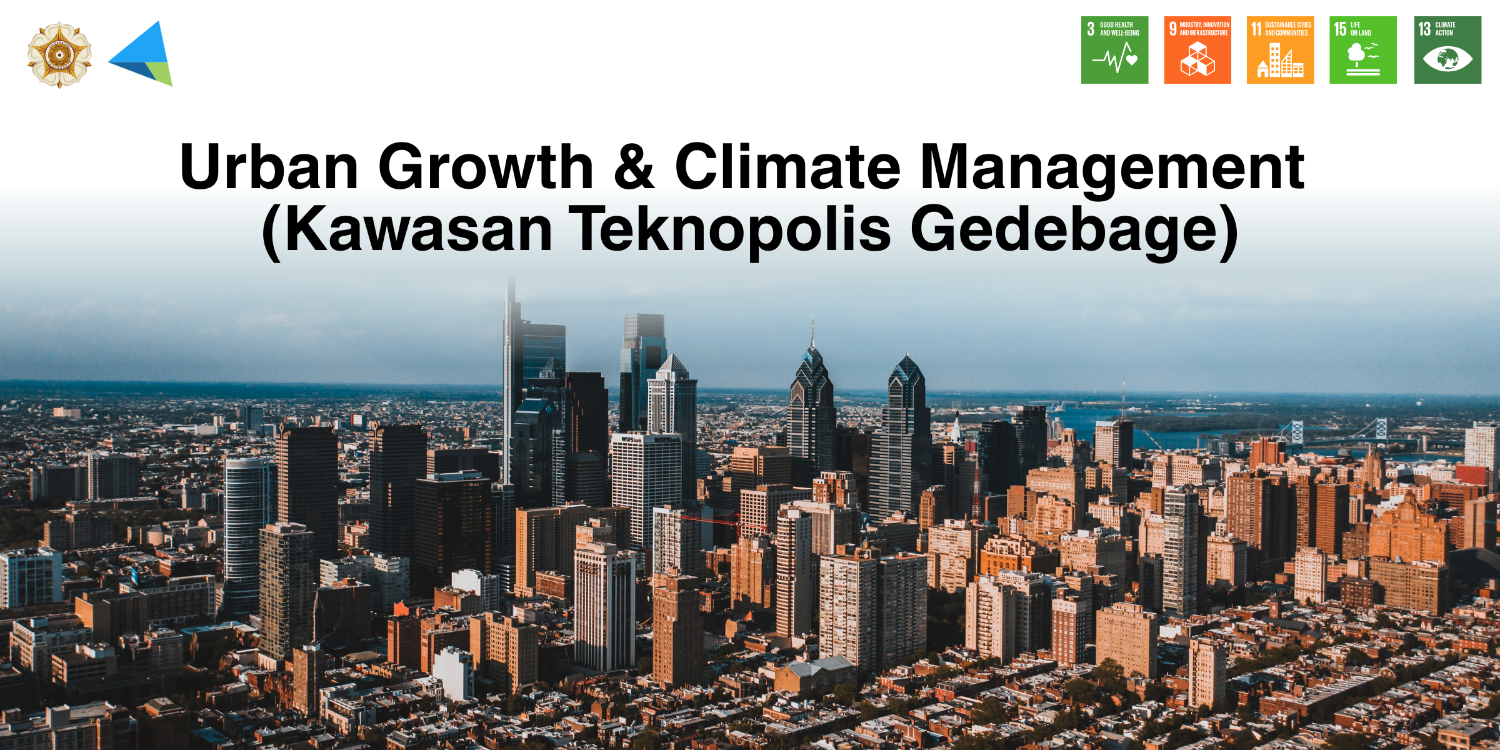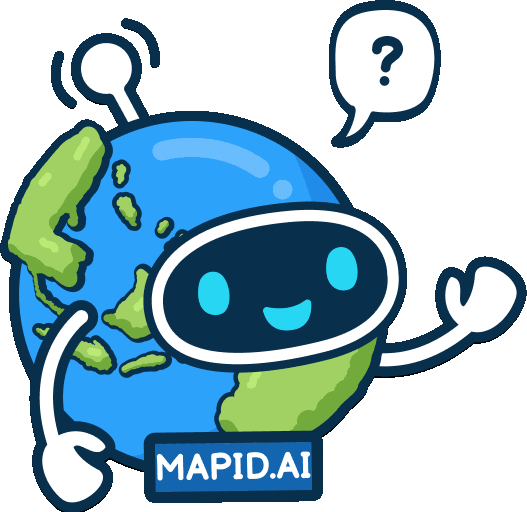Latar Belakang
Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya akan sejarah dan warisan budaya. Salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi adalah Kotabaru, yang hingga saat ini tetap menjadi saksi bisu perkembangan kota serta berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kawasan ini memiliki karakteristik arsitektur dan tata kota yang unik, serta menjadi bagian dari Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan perkembangan zaman dan meningkatnya minat wisata sejarah, penting untuk merancang rute walkingtour yang efektif untuk wisata edukasi berbasis sejarah. Dalam hal ini, teknologi Sistem Informasi Geografis (GIS) berperan dalam membantu analisis dan pemetaan rute terbaik bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Kotabaru.
Sejarah dan Perkembangan Kotabaru
Kotabaru Yogyakarta memiliki latar belakang sejarah yang bermula sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya investasi dari Eropa dan kebutuhan akan permukiman eksklusif bagi para pejabat dan elite kolonial, Kotabaru dibangun pada tahun 1911. Kawasan ini dirancang sebagai lingkungan permukiman baru yang modern dengan mengikuti konsep tata kota yang sistematis.
Kotabaru dibangun dengan mengadopsi konsep Garden City, sebuah konsep tata kota yang berkembang di Eropa pada saat itu. Dengan konsep ini, Kotabaru dirancang sebagai kawasan hunian elite yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti taman, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Arsitektur bangunan di kawasan ini juga khas dengan gaya Landhuis yang menunjukkan pengaruh kolonial yang kuat. Rumah-rumah di Kotabaru umumnya memiliki halaman luas, serambi, dan atap tinggi yang dirancang untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Indonesia. Tata ruang yang terencana menjadikan Kotabaru sebagai salah satu kawasan permukiman yang paling eksklusif pada masanya.

Peran Kotabaru dalam Sejarah Perjuangan Bangsa
Selain menjadi kawasan permukiman kolonial, Kotabaru juga memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu peristiwa bersejarah yang terkait dengan kawasan ini adalah pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke Yogyakarta pada tahun 1946. Beberapa bangunan di Kotabaru kemudian digunakan sebagai kantor kementerian untuk mendukung jalannya pemerintahan di masa revolusi.
Tidak hanya itu, Kotabaru juga menjadi lokasi penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Serbuan Kotabaru pada tahun 1949. Peristiwa ini merupakan bagian dari rangkaian perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan agresi militer Belanda yang berusaha merebut kembali Yogyakarta. Pertempuran yang terjadi di kawasan ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Kotabaru dalam sejarah perlawanan terhadap penjajah.
Kotabaru sebagai Kawasan Cagar Budaya
Seiring dengan perjalanan waktu, Kotabaru tetap mempertahankan identitasnya sebagai kawasan bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Saat ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Kotabaru sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB) yang harus dijaga kelestariannya. Status ini bertujuan untuk melindungi warisan arsitektur dan sejarah yang terdapat di kawasan tersebut agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Sebagai kawasan cagar budaya, Kotabaru tidak hanya berfungsi sebagai area permukiman, tetapi juga menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik. Banyak bangunan di kawasan ini yang masih berdiri kokoh dan tetap digunakan, baik sebagai rumah tinggal, institusi pendidikan, maupun tempat usaha. Oleh karena itu, Kotabaru menjadi salah satu lokasi yang ideal untuk wisata berbasis sejarah dan edukasi, terutama dalam bentuk walking tour yang memungkinkan wisatawan untuk menikmati langsung keindahan arsitektur dan sejarah kawasan ini.
Pentingnya Rute Jelajah Berbasis GIS untuk Wisata Walking Tour
Dengan meningkatnya minat terhadap wisata sejarah, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu wisatawan menjelajahi Kotabaru dengan lebih efektif. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis rute berbasis GIS. GIS merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk menganalisis data spasial dan merancang rute yang optimal berdasarkan berbagai parameter seperti jarak, kondisi jalan, aksesibilitas, serta keberadaan titik-titik wisata bersejarah yang ingin dikunjungi.
Dengan menggunakan GIS, perencanaan rute wisata dapat dilakukan secara lebih ilmiah dan berbasis data. Hal ini memungkinkan wisatawan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih maksimal dalam menjelajahi Kotabaru tanpa harus menghadapi kendala seperti kebingungan arah atau pemilihan rute yang kurang efisien. Selain itu, teknologi GIS juga dapat digunakan untuk menyajikan informasi tambahan tentang bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kawasan ini, sehingga wisatawan dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai latar belakang dan sejarah tempat yang mereka kunjungi.
Metodologi
Penelitian ini dilakukan di Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Pembuatan rute wisata dilakukan dengan menggunakan analisis jaringan (network analysis) melalui Plugin ORS QGIS dan analisis isochrone untuk mengetahui jarak waktu dari titik keberangkatan menggunakan GEOMAPID. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup titik koordinat bangunan cagar budaya serta jaringan jalan di kawasan Kotabaru.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei lapangan untuk memperoleh titik koordinat setiap bangunan cagar budaya yang menjadi objek wisata. Sementara itu, data jaringan jalan diperoleh dari openrouteservices, yang menyediakan informasi terkait rute dan aksesibilitas di kawasan tersebut. Selain menggunakan analisis berbasis GIS, pembuatan rute dari satu objek ke objek lainnya dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui jarak dan waktu tempuh yang paling efisien. Dengan metode ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat menggambarkan rute optimal yang tidak hanya efisien dari segi waktu dan jarak, tetapi juga mempertimbangkan aspek kenyamanan dan pengalaman wisatawan dalam menjelajahi Kotabaru.

Hasil dan Pembahasan
Kotabaru di Yogyakarta merupakan kawasan perumahan yang dibangun pada era kolonial Belanda setelah Perang Dunia I, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VII. Kawasan ini awalnya diperuntukkan sebagai pemukiman eksklusif bagi orang Eropa yang bekerja di bidang pemerintahan dan perkebunan. Dibangun dengan konsep Garden City, Kotabaru memiliki tata ruang yang tertata rapi dengan boulevard, ruang terbuka hijau, serta pepohonan rindang yang memberikan kesan asri dan nyaman. Secara administratif, kawasan ini berada di Kecamatan Gondokusuman dan memiliki batas wilayah yang jelas, dengan Sungai Code di sebelah barat dan Stasiun Lempuyangan di sebelah selatan.
Seiring perjalanan waktu, Kotabaru mengalami berbagai perubahan fungsi, terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, kawasan ini dialihfungsikan menjadi pusat administrasi, tangsi militer, dan gudang. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di sini adalah Pertempuran Kotabaru pada 7 Oktober 1945, ketika para pemuda Indonesia berusaha melucuti senjata tentara Jepang. Pasca-kemerdekaan, banyak bangunan di Kotabaru yang beralih fungsi menjadi sekolah, perkantoran, dan tempat usaha. Untuk menjaga nilai sejarah dan arsitekturnya, kawasan ini kini ditetapkan sebagai Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Perda DIY No. 6 Tahun 2012, yang mengatur pelestarian bangunan dengan gaya arsitektur kolonial dan Indis.
Isochrone Walkingtour Kotabaru Heritage
Analisis peta isochrone jalan kaki di Kotabaru dilakukan dengan mengambil titik pusat pada koordinat Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Pemilihan titik ini didasarkan pada lokasinya yang strategis di pusat Kotabaru serta ketersediaan fasilitas parkir yang memungkinkan sebagai titik awal walking tour. Isochrone dibuat berdasarkan durasi perjalanan kaki selama 5 menit dan 10 menit untuk melihat jangkauan aksesibilitas terhadap cagar budaya di wilayah tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam radius 5 menit berjalan kaki, hanya 6 dari 16 cagar budaya yang dapat dijangkau, yaitu Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Museum Dharma Wiratama, RS Bethesda, SMA 3 Yogyakarta, dan SMP 5 Yogyakarta. Sementara itu, pada isochrone 10 menit berjalan kaki, seluruh titik cagar budaya yang ada di Kotabaru dapat terjangkau, menunjukkan bahwa area ini memiliki konektivitas pejalan kaki yang cukup baik dalam cakupan waktu yang lebih luas.

Analisis Jaringan Rute Walkingtour Kotabaru Heritage
Hasil analisis jaringan menunjukkan bahwa Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kotabaru memiliki jaringan jalan yang cukup baik dengan beberapa objek cagar budaya yang saling berdekatan.
Dalam pembuatan rute walking tour KCB Kotabaru, telah diidentifikasi 16 titik objek cagar budaya yang menjadi ciri khas kawasan ini dan dapat dikunjungi dalam satu perjalanan. Penentuan rute dilakukan melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui jarak antar objek serta estimasi waktu tempuh.
Dari hasil observasi, waktu total yang dibutuhkan untuk menjelajahi seluruh rute dengan berjalan kaki adalah sekitar 40 menit, dengan asumsi pengunjung berjalan tanpa berhenti di setiap titik. Namun, jika setiap objek dikunjungi dengan durasi 5 menit per titik, maka total durasi walking tour menjadi sekitar 120 menit.
Rute ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang optimal bagi pengunjung dalam menikmati kekayaan sejarah dan arsitektur khas Kotabaru.

Rincian Rute Hasil Network Analysis
1. Gedung Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Bangunan ini menjadi titik awal walkingtour karena memiliki parkir kendaraan yang cukup dan pengunjung mendapatkan informasi pariwisata KCB Kotabaru.
Bangunan ini memiliki sejarah yang erat dengan rute gerilya Jenderal Sudirman. Setelah bergerilya selama tujuh bulan, tempat ini menjadi titik akhir perjalanan beliau. Sebelumnya, bangunan ini adalah kediaman Jenderal Urip Sumoharjo. Saat ini, bangunan telah mengalami beberapa perubahan, terutama pada bagian depan gedung induk serta sayap kanan dan kiri.
Di halaman depan, terdapat sebuah monumen yang menandai bahwa tempat ini pernah menjadi lokasi akhir rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pernyataan tersebut diabadikan dalam lempengan tembaga yang bertuliskan: TETENGER Jalan Suroto.
Sebelum difungsikan sebagai Kantor Dinas Pariwisata dan Budaya, bangunan ini pernah digunakan sebagai Kantor Transmigrasi. Meskipun telah beralih fungsi, struktur aslinya masih terjaga dengan baik. Bangunan ini memiliki denah berbentuk segi empat dengan orientasi menghadap tenggara. Terdiri dari tiga unit, bagian tengahnya beratap kerucut, sementara kedua sisinya menggunakan atap limasan.
Dari segi arsitektur, bangunan ini mencerminkan gaya peralihan yang memadukan unsur klasik, modern, dan tropis. Gaya klasik terlihat pada atap kerucut yang curam serta hiasan vitrin pada jendela penerang. Elemen modern tampak pada bentuk dan ornamen yang sederhana. Sementara itu, unsur tropis terlihat pada dinding yang dipenuhi jendela serta ventilasi vertikal untuk sirkulasi udara. Jendela-jendela ini juga dilengkapi dengan tritisan, sedangkan bagian bawah dinding (subasemen) dilapisi kerakal.
Bangunan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. PM.07/PW.007/MKP/2010. Saat ini, Kantor Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta berlokasi di Jalan Suroto No. 11, Kotabaru, Yogyakarta.
2. Museum Dharma Wiratama

Bangunan ini berdiri pada tahun 1904, sebagai Rumah Dinas Administrasi Perkebunan Kolonial Belanda yang membawahi Jawa Tengah dan Yogyakarta hingga tahun 1942. Pada tahun 1942 digunakan sebagai markas SyudSyudocan. Tahun 1945 s.d. 1949 sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Tahun 1961 s.d. 1982 sebagai markas Korem 072 Pamungkas, 1982 sampai sekarang sebagai Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Per.Men Budpar RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011. Museum TNI AD terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 75 Yogyakarta.
3. Rumah Sakit Bethesda

Rumah Sakit Petronella (Zendingziekenhuis Petronella) didirikan oleh dr. Jan Gerrit Scheuer di Gondokusuman dengan bantuan lahan dari Sultan Hamengkubuwono VII. Nama "Petronella" diambil dari istri seorang pensiunan pendeta yang menyumbangkan dana untuk pembangunan rumah sakit ini.
Awalnya, dr. Scheuer membuka klinik sederhana di Bintaran sebelum akhirnya pindah ke Gondokusuman pada tahun 1901 karena meningkatnya jumlah pasien. Pada tahun 1900, Sultan menyediakan tanah untuk pembangunan rumah sakit berkapasitas 150 pasien. Rumah sakit ini dikenal sebagai Rumah Sakit Tulung karena memberikan layanan kesehatan gratis.
Pada 1906, dr. Scheuer kembali ke Belanda dan digantikan oleh dr. H.S. Pruys, yang memperkenalkan sistem rujukan dengan mendirikan rumah sakit pembantu di desa-desa. Di bawah kepemimpinan dr. J. Offringa (1924-1925), kapasitas rumah sakit meningkat menjadi 475 tempat tidur dan ditambahkan fasilitas seperti mobil rawat jalan.
Dampak ekonomi akibat Perang Dunia pada 1930-an menyebabkan pengurangan bantuan dana, penutupan rumah sakit pembantu, dan penghentian operasional mobil rawat jalan. Sebagai gantinya, poliklinik rawat jalan didirikan di beberapa lokasi. Pada 1936, rumah sakit ini membangun sanatorium tuberkulosis dan bangsal bersalin.
Saat pendudukan Jepang, rumah sakit diambil alih dan berganti nama menjadi Jogjakarta Tjuo Bjoin. Setelah kemerdekaan, rumah sakit kembali menjadi milik gereja dan berganti nama menjadi Roemah Sakit Poesat sebelum akhirnya pada 28 Juni 1950 resmi bernama Rumah Sakit Bethesda.
Bangunan rumah sakit memiliki arsitektur khas dengan bentuk limasan, menghadap utara, serta dilengkapi ventilasi untuk pendinginan alami. Saat ini, Rumah Sakit Bethesda terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 70, Yogyakarta, dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011.
4. Rumah Sakit DKT Soetarto

Terbagi menjadi Bangsal Umrinkes, Bangsal Urtuud, Bangsal Kiran, Bangsal Husada, koperasi, kamar jenazah, Bangsal administrasi Kesehatan, Bangsal Urusan Dalam, UGD dan Poliklinik. Gaya Arsitektur pada massa bangunan RUUTD ini merupakan gaya arsitektur Kolonial. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit yang dinaungi oleh TNI AD. Sejarah berdirinya gedung Rumah Sakit Dr. Soetarto (Rumah Sakit DKT) dimulai pada tahun 1913 sebagai Rumah Sakit Militer Belanda (KNIL). Pada tahun 1974 masa clash I digunakan untuk asrama ataupun pusat kegiatan perawat palang merah tentara. Setelah pengakuan kedaulatan kedaulatan Indonesia oleh belanda pada tahun 1989, bangunan tersebut diambil alih oleh tentara Indonesia dan dijadikan untuk rumah sakit tentara (DKT) oleh TNI sampai sekarang. Penggubung antar bangunan dalam komplek ini meggunakan doorlop.
Dibangun pada masa pemerintah Hindia Belanda, pada awalnya memang sudah dimanfaatkan sebagai rumah sakit militer Belanda dan dibangun pada tahun 1913. Adapun yang menjadi pimpinan Tempat Perawatan Tentara (TPT) tersebut adalah Letkol Dr. R. Soetarto dan Kapten Dr. Amino Gondo Utomo. Sekitar tahun 1951, TPT yang semula berlokasi di depan RS. Bethesda dan Markas Kesehatan Brigade yang berlokasi di Jl. Widodo Kotabaru dipindahkan ke Jl. Juwadi no.19 Kotabaru, bekas Militer Hospital Belanda yang dibangun tahun 1913, yang sebelumnya ditempati Batalyon X, dengan nama sebutan Kesatuan DKT ST.13 dan Rumah Sakit Tentara DK ST.13 dibawah pimpinan Letkol Dr. R. Soetarto (DKT ST.13 : Dinas Kesehatan Tentara Sub Territorium 13).
Pemilik/pengelola bangunan ini menerima penghargaan Pelestari Warisan Budaya / Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017.
5. SMA Bopkri 1 Yogyakarta

Gedung SMA BOPKRI I Yogyakarta awalnya dibangun pada tahun 1922 sebagai Christelijk MULO School, sebuah sekolah lanjutan setingkat SMP. Fungsi ini bertahan hingga 1941, sebelum dihentikan akibat Perang Dunia II dan pendudukan Jepang pada 1942-1945, ketika gedung ini dialihfungsikan sebagai tangsi militer.
Pada 31 Oktober 1945, gedung ini digunakan sebagai pusat pendidikan Militer Academie (MA) Yogyakarta, sementara asrama kadetnya berada di Normal School (sekarang SMP Negeri 5 Yogyakarta). Hingga 1950, MA Yogyakarta telah meluluskan dua angkatan sebelum akhirnya ditutup sementara karena alasan teknis.
Tahun 1950-1951, bangunan ini digunakan oleh SMA Negeri 5. Mulai tahun 1951 hingga sekarang, gedung ini menjadi tempat bagi SMA BOPKRI I Yogyakarta.
Secara arsitektural, gedung ini bergaya Indis dengan atap kampung bertipe tinggi, dirancang sejak awal untuk kenyamanan kegiatan belajar. Ciri khasnya meliputi jendela tingkat di bagian depan serta elemen Eropa pada dinding, pintu, dan jendela, meski minim ornamen. Gedung ini memiliki keterkaitan spasial dengan kawasan cagar budaya Kotabaru, yang dulunya merupakan permukiman warga Belanda di pusat Yogyakarta.
SMA BOPKRI I Yogyakarta telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No. PM25/PW.007/MKP/2007 dan berlokasi di Jalan Wardani No. 2, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta.
6. Asrama Kompi Kotabaru

Asrama Kompi Kotabaru terletak di Jl. Atmosukarto No. 9, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta, berdekatan dengan Stadion Kridosono dan SMA BOPKRI 1 Yogyakarta. Bangunan ini telah berfungsi sebagai fasilitas militer sejak didirikan pada 1920-an di masa Pemerintahan Hindia Belanda. Saat itu, dikenal sebagai Magazijn van Oorlog atau asrama militer, yang dibangun sebagai bagian dari sistem pertahanan di Kotabaru. Saat ini, asrama ini berada di bawah KOREM 072 dan masih digunakan sebagai tempat tinggal prajurit TNI.
Arsitektur bangunan ini berciri khas Eropa, selaras dengan gaya bangunan lain di kawasan Kotabaru. Kompleksnya terdiri dari empat baris bangunan berderet dengan ruang-ruang yang lebar dan memanjang, sesuai fungsinya sebagai barak. Meski masih terawat dengan baik, beberapa bagian atap telah mengalami penambahan.
Di dalam kompleks ini terdapat monumen peringatan Pertempuran Kotabaru yang terjadi pada 7 Oktober 1945. Peristiwa ini merupakan perjuangan Tentara Rakyat Indonesia dan para pemuda Yogyakarta dalam melawan tentara Jepang yang masih bertahan setelah proklamasi kemerdekaan. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Per.Men Budpar RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011.
7. SMP Negeri 5 Yogyakarta

Gedung SMP 5 Yogyakarta terletak di Jl. Wardani No. 1, Yogyakarta. Bangunan ini berdiri sejak zaman Belanda dan digunakan untuk MULO dan Normaalschool (Pendidikan Guru Bumiputra) yang dibangun tahun 1923. Pada masa awal revolusi atau pemerintahan RI digunakan sebagai asrama Militer Akademi sampai dengan tahun 1948. Arah hadap bangunan SMP 5 saat ini ke selatan.Denah bangunan utama berjajar tiga yaitu sayap utara, tengah, dan sayap selatan. Selain itu masih ada beberapa bangunan berdiri secara terpisah/mandiri. Kompleks bangunan sebanyak 43 buah ini terdiri atas ruang-ruang antara lain kelas, rumah dinas, ruang lain (ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah, ruang TU, ruang BP, ruang perpustakaan, mushola, ruang tamu, laboratoium, ruang koperasi aula, dan lainnya. Secara arsitektural, bangunan-bangunan yang berada SMP 5 dikelompokkan menjadi dua yaitu berlantai satu dan berlantai dua. Ciri-ciri bangunan yang menonjol yaitu bangunanya tinggi, besar, mempunyai halaman luas, jendela dan pintu besar dengan krepyak langit-langit tinggi, mempunyai roster pada dinding-dindingnya. Sebagian besar fungsi ruang adalah sebagai kelas. Fungsi ruang lainnya sebagai sarana penunjang seperti ruang olahraga dan rumah dinas kepala sekolah atau guru. Gedung-gedung yang ada dibangun dalam beberapa periode. Pada awalnya ruang terbuka cukup luas, saat ini ruang terbuka menyempit karena pembangunan bangunan baru. Genteng bangunan lama sudah beberapa kali mengalami penggantian. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Per.Men Budpar RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011.
8. SMA Negeri 3 Yogyakarta

Gedung SMA Negeri 3 Yogyakarta awalnya digunakan untuk Algemeene Middelbare School (AMS) afd. B., sekolah menengah atas yang lebih tinggi dari MULO. Bangunan ini didirikan pada tahun 1919. Selama pendudukan Jepang, sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Menengah Tinggi (SMT) dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian A (ilmu kebudayaan) dan bagian B (ilmu alam).
Pada 19 September 1942, guru dan murid yang mengalami tekanan dari Jepang membentuk organisasi Padmanaba. Seiring bertambahnya jumlah siswa, pada tahun 1946/1947, sekolah ini dipisah, dengan bagian A di Jalan Pakem dan bagian B di Jalan Jati Kotabaru. Saat Agresi Militer Belanda I (1947), sekolah sempat ditutup selama tiga bulan karena digunakan sebagai markas pejuang. Setelahnya, sekolah mengalami lonjakan murid sehingga dibuka sekolah darurat dan sekolah pejuang. Pada Agresi Militer II, sekolah kembali ditutup dan digunakan sebagai markas tentara Belanda. Banyak anggota Padmanaba bergabung dengan Tentara Pelajar (TP) dan gugur dalam Pertempuran Kotabaru, seperti Faridan M. Noto, Suroto, Kunto, dan lainnya.
Pada tahun 1956, sekolah ini berganti nama menjadi SMA IIIB dan pada tahun 1964 resmi menjadi SMA Negeri 3 Yogyakarta. Secara arsitektural, bangunan ini memiliki ciri khas kolonial dengan bangunan tinggi, besar, jendela dan pintu berukuran besar dengan krepyak, serta langit-langit tinggi. Bagian depan bangunan utama memiliki tiang bergaya Yunani/Romawi. Denahnya terdiri dari dua bangunan utama yang berjajar dengan halaman luas di tengah, sementara fasilitas tambahan seperti laboratorium, ruang olahraga, dan lapangan sepak bola berada di sisi bangunan utama. Bangunan ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Per.Men Budpar RI No. PM.07/PW.007/MKP/2010 dan terletak di Jalan Yos Sudarso No. 7, Yogyakarta.
9. Rumah Indies Sajiono

Jalan Sajiono di Kotabaru, Yogyakarta, dikenal dengan deretan rumah-rumah bergaya arsitektur Indis yang merupakan peninggalan masa Hindia Belanda. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan ini memiliki ciri khas yang serupa, seperti atap limasan dengan kemiringan sekitar 40-45 derajat, serta penggunaan genting vlam berwarna tanah liat sebagai penutup atap.
Salah satu contoh bangunan dengan gaya arsitektur Indis yang masih terjaga adalah rumah di Jalan Sajiono Nomor 7. Bangunan ini memiliki lisplang kayu asli, pintu dengan rangka kayu dan panil kaca, serta jendela ganda—bagian dalam menggunakan kayu berteralis dan bagian luar berupa panil kayu kombinasi krepyak. Struktur dan bentuk rumah ini identik dengan bangunan lain di sepanjang jalan, seperti yang terdapat di Jalan Sajiono Nomor 1, 5, 9, 11, 13, dan 15. Keberadaan bangunan-bangunan ini memperkuat karakter kawasan sebagai salah satu area bersejarah dengan arsitektur khas kolonial.
10. Museum Sandi

Museum Sandi terletak di Jalan F.M. Noto No. 21, Kotabaru, Yogyakarta. Bangunan ini awalnya merupakan rumah tinggal bagi masyarakat Eropa di kawasan Kotabaru, yang mulai berkembang pada tahun 1920. Dengan arsitektur Indis khas Kotabaru, bangunan ini memiliki dua lantai dengan pintu dan jendela besar serta balkon di lantai dua yang menambah kesan megah.
Setelah Kemerdekaan Indonesia, banyak bangunan di Yogyakarta mengalami perubahan fungsi, termasuk gedung ini. Pada tahun 1946, ketika ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta, bangunan ini digunakan sebagai Kantor Kementerian Luar Negeri RI. Setelah ibu kota kembali ke Jakarta, gedung ini dikelola oleh Pemerintah DIY dan beberapa kali beralih fungsi, termasuk sebagai kantor dan perpustakaan.
Pada tahun 2006, atas inisiatif Kepala Lembaga Sandi Negara RI, Mayjen TNI Nachrowi Ramli, dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, bangunan ini ditetapkan sebagai Museum Sandi. Museum ini diresmikan dan mulai beroperasi pada 29 Januari 2014. Museum Sandi menampilkan sejarah persandian di dunia dan Indonesia, termasuk koleksi peralatan sandi yang digunakan pada Agresi Militer Belanda I dan II. Museum ini juga mengabadikan sejarah berdirinya institusi pengamanan berita rahasia pada awal kemerdekaan Indonesia, yang didirikan oleh Bapak Persandian Indonesia, dr. Roebiono Kertopati.
11. Masjid Syuhada

Perkembangan sejarah Masjid Syuhada Tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangaan pejuang Indonesia melawan tentara pendudukan Jepang. Peristiwa itu telah memakan korban 21 orang pejuang yang sekarang namanya diabadikan menjadi nama jalan di kawasan Kotabaru. Pembangunan masjid ini pada awalnya bertujuan sebagai monumen sejarah para syuhada yang gugur pada waktu itu. Namun seiring dengan kebutuhan akan tempat peribadatan, maka masjid ini digunakan sebagai tempat ibadah masyarakat muslim di Kotabaru.
Istilah syuhada sudah dikenal masyarakat, artinya orang-orang yang mati syahid atau gugur di jalan Allah. Nama lengkap masjid ini adalah Masjid Peringatan Syuhada. Mengingat terlampau panjang, maka seringkali disebut Masjid Syuhada saja. Pembangunan Masjid Syuhada dimulai dengan pembentukan panitia pada tanggal 14 Oktober 1949. Peletakan batu pertama dilakukan tanggal 23 September 1950 dan peresmian penggunaan dilakukan pada tanggal 20 September 1952. Jadi sejak peletakan batu pertama sampai peresmiannya, pembangunan masjid ini memakan waktu dua tahun. Tanggal 20 Sepetember 1952 dijadikan tanggal kelahiran (milad) Masjid Syuhada.
Tanah yang akan dibangun masjid merupakan pemberian dari Sultan Hamengku Buwono IX. Tanah ini terletak di sebelah timur Kali Code. Lokasi tanah ini berada diantara dua jembatan yaitu Jembatan Kridonggo ( kreteg Kewek) dan Jembatan Gondolayu. Masjid Syuhada dirancang terdiri atas 3 lantai. Atap masjid sebagai puncak masjid terdapat kupel (mustoko) besar sebagai kubah masjid. Bagian tengah merupakan ruangan untuk shalat dan bagian bawah berupa ruangan yang digunakan sebagai kantor dan perpustakaan masjid.
12. Gereja HKBP Yogyakarta

Gereja HKBP terletak di Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 22, Yogyakarta. Hari lahir Gereja HKBP ditandai dengan dibaptisnya Jacobus Tampubolon dan Simon Siregar oleh misionaris van Asselt di Sipirok, Tapanuli Selatan pada tanggal 7 Oktober 1861. Bangunan Gereja didirikan pada tahun 1923. Pada awalnya merupakan bangunan Gereformeede Kerk Djogja. Bangunan gereja kemudian difungsikan sebagai tempat dansa dan musik orang – orang Belanda (Muziekenten). Pada masa pendudukan Jepang bangunan ini dipakai sebagai rumah tahanan wanita Belanda (Internerens Camp Belanda). Pada wal tahun 1940-an banyak orang Batak datang ke Pulau Jawa, termasuk di Yogyakarta. Para pemuda datang ke Yogyakarta pada umumnya melanjutkan pendidikan di AMS (Algemene Middelbare School). Pada awalnya orang – orang Batak mengikuti kebaktian di gereja- gereja lain di Yogyakarta (biasanya di Gereja Margamulyo). Pada tanggal 7 April 1946, orang Batak di Yogyakarta untuk pertama kalinya mengadakan kebaktian yang dihadiri sekitar 8 keluarga serta beberapa pemuda dan anak – anak di jalan pakuningratan No.6 Yogyakarta. Kebaktian ini mengatasnamakan HKBP cabang Yogyakarta walaupun secara yuridis formal HKBP di Yogyakarta belum ada. Pertemuan kotbah tanggal 7 April 1946 inilah yang dijadikan hari lahir gereja HKBP Yogyakarta . kebaktian pertama kali dipimpin oleh seorang jemaat yatu J.A Lumbantobing, yang dihadiri antara lain oleh keluarga W. Hutabarat, Aritonang, O. Hutabarat, J.A Lumbantobing dan Siregar. Tempat kebaktian HKBP pertama kali adalah di Jl. Pakuningratan No. 6 Yogyakarta. Dengan meningkatnya jumlah jemaat, maka HKBP Yogyakarta harus mengusahakan tempat kebaktian yang lebih luas. Dari Jl. Pakuningratan No.6 pidah ke SD Ungaran Kotabaru. Pada tanggal 13 Oktober 1946 pindah ke Gereja Margamulya, pindah lagi ke Balai Pertemuan Kristen (BPK) Gondokusuman No. 41 milik Gereja Kristen Jawa Yogyakarta. Pendeta Darmo memberitahukan bahwa di lingkungan BPK masih ada tempat kosong yang dapat digunakan untuk kebaktian. Agar dapat menggunakan tempat tersebut, HKBP harus membayar 10 Gulden seiap bulan untuk biaya perawatan dan pengaturan gedung serta tunjangan bagi pegawai BPK. Dari BPK tempat kebaktian pindah ke Sekolah Menengah Kristen Terban Taman No. 33. Pada tanggal 17 November 1946 tempat kebaktian kembali lagi ke BPK, karena BPK tidak jadi digunakan asrama mahasiswa teologia. Komplek bangunan gereja terdiri dari beberpa bagian, bangunan utama merupakan bangunan lama sebagai tempat ibadah, sisi utara terdapat aula dengan 2 lantai yang merupakan bangunan baru, dan sisi timur serta selatan terdapat bangunan baru yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung. Gereja menghadap ke Barat dengan denah berbentuk variasi segi 6 dengan ruang utama berukuran 22×18,6 m. Bangunan ini ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Per.Men Budpar RI No. PM.89/PW.007/MKP/2011.
13. Pastoran

Sekitar tahun 1920, wilayah Kotabaru masih berupa kampung pinggiran. Rencananya, kampung ini akan menjadi kompleks perumahan bagi orang-orang Belanda yang tinggal di Yogyakarta. Pembuatan kompleks perumahan ini membuat warga kampung terpaksa menyingkir. Tetapi mereka tetap memperoleh ganti rugi. Di kampung ini belum ada orang yang beragama Katolik. Kalau pun ada, satu atau dua orang itu menjadi Katolik karena pewartaan dari Paroki Senopati, Paroki St. Fransiskus Xaverius Kidul Loji.
Awal kegiatan misi katolik di sekitar Kotabaru dimulai dengan kehadiran Romo Fransiskus Strater, SJ sekitar tahun 1918. Sebagai seorang misionaris awal, Romo Strater, SJ melakukan beberapa langkah berikut. Pertama, Romo Strater menyewa rumah Tuan Perquin -di depan Masjid Syuhada sekarang- untuk dijadikan pastoran, tempat mengajar agama, tempat ibadah, dan novisiat. Kedua, Romo Strater membeli tanah lapang dan kuburan untuk pendirian rumah pembinaan Jesuit yang kemudian diberi nama Kolese Santo Ignatius ( Kolsani).
14. Gereja Katolik Santo Antonius Padua

Perintis pendirian Gereja Santo Antonius Kotabaru adalah Romo F. Strater. Sebelum Gereja tersebut berdiri, Romo F. Strater merintis pendirian Kolsani (Kolese Santo Ignatius) dan Novisiat Kolsani yang telah dimulai pada 18 Agustus 1922. Kolsani ini juga mempunyai kapel yang terbuka untuk umum. Romo F. Strater memandang perlu didirikan gereja yang lebih besar dan representatif, karena perkembangan umat yang terus bertambah.
Pendirian gereja mengharus syarat bahwa gereja tersebut diberi nama St Antonius van Padua. Pembangunan gereja tersebut selesai pada 1926. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 Kolsani menjadi tempat penampungan suster-suster dan wanita-wanita Belanda interniran. Seminari Tinggi yang letaknya di sebelah barat gereja menjadi kantor tentara Jepang dan Gereja Santo Antonius Kotabaru menjadi gudang dan kemudian tidak berfungsi lagi menjadi gereja.
Pada 1944, pastur pertama Kotabaru Rama Strater SJ dibunuh oleh tentara Jepang karena mengadakan rapat rahasia bagi beberapa kepala sekolah Kanisius seluruh Yogyakarta. Oleh karena Gereja Kotabaru sudah tidak berfungsi lagi menjadi gereja maka kemudian dicarikan sebuah rumah kuno berbentuk joglo di daerah Kumetiran. Rumah ini kemudian dijadikan gereja.
Setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia tahun 1945, maka Kolsani dan Gereja Santo Antonius Kotabaru berfungsi kembali menjadi gereja seperti semula. Gereja ini menghadap ke arah timur dengan bentuk memanjang. Atapnya berbentuk limasan, demikian pula kanopinya. Di bagian depannya terdapat sebuah menara. Bangunannya terdiri dari empat bagian atap. Atap yang paling tinggi adalah atap menara lonceng di bagian tengah depan. Lebih rendah dari bagian atap menara adalah atap bangunan utama bagian tengah yang menaungi ruang tengah. Sedangkan ruang altar yang berada di sebelah barat dinaungi oleh atap yang lebih rendah.
Atap yang paling rendah adalah atap yang menaungi tepi kanan dan kiri ruang ibadah. Plafonnya berupa tembok berbentuk sungkup yang sangat tinggi. Tiang terbuat dari semen cor sebanyak 16 buah. Di sisi selatan terdapat ruang untuk mempersiapkan upacara dan merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat upacara. Di sisi utara terdapat ruang pengakuan dosa. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Per.Men Budpar RI No. PM.07/PW.007/MKP/2010. Gereja St. Antonius Yogyakarta terletak di Jl. I Dewa Nyoman Oka No. 18 Yogyakarta.
15. SD Negeri Ungaran

Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan digunakan untuk Sekolah HIS. Ssetelah perang Kotabaru, 13 Oktober 1945, digunakan sebagai Militer Akademi (MA), kemudian difungsikan sebagai Sekolah Rakyat (SR) latihan dan Sekolah Guru Putri (SGP).
Pada 5 Juli 1949 berubah menjadi Sekolah Rakyat (SR) Ungaran dan sekarang bernama SD Ungaran. Bangunan berbentuk memanjang terdiri dari tujuh ruang kelas dan satu ruang kantor. Atap bangunan bentuk limasan dengan kemiringan yang tajam. Bangunan terkesan rendah karena atap dengan teras yang relatif lebar menjadi satu, bahan atap genteng. Pintu dan jendela terbuat dari kayu jati dengan berdaun dua bermotif krepyak.
Bangunan tambahan di bagian depan membujur dari barat ke timur menghadap ke selatan menutupi bangunan lama. Bangunan tambahan terdiri atas dua lantai, pada lantai bawah difungsikan untuk ruang kelas satu, pos keamanan, dan pintu gerbang utama, sedangkan lantai atas untuk aula dan ruang les. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya melalui Per.Men Budpar RI No. PM25/PW.007/MKP/2007. SD Ungaran terletak di Jl. Patimura, Kotabaru, Gondokusuman.
16. Babon ANIEM

Babon ANIEM adalah gardu listrik peninggalan masa kolonial yang terletak di persimpangan Jalan F.M. Noto, Kotabaru, Yogyakarta. Bangunan ini merupakan bagian dari jaringan listrik yang dibangun oleh ANIEM (Algemene Nederlandsch Indische Electrisch Maatschapij), perusahaan listrik swasta Hindia Belanda.
Pembangunan jaringan listrik di Yogyakarta dimulai pada tahun 1914, dengan Kotabaru sebagai salah satu kawasan prioritas karena merupakan permukiman masyarakat Eropa. Selain listrik, kawasan ini juga telah dilengkapi dengan infrastruktur modern seperti saluran air bersih, telepon, dan drainage. Babon ANIEM di Kotabaru dibangun sekitar tahun 1918 sebagai pusat pengatur dan pembagi daya listrik.
Di Yogyakarta, masih terdapat tiga Babon ANIEM yang tersisa, yaitu di Kotabaru, depan Taman Parkir Abu Bakar Ali, dan Pasar Kota Gede. Listrik pertama kali dialirkan ke Yogyakarta pada tahun 1918 dari pembangkit listrik di Tuntang, Semarang, setelah pembangunan jaringan listrik dari Semarang yang dimulai pada tahun 1904. Pada tahun 1919, meningkatnya permintaan listrik mendorong ANIEM membangun pembangkit listrik tenaga diesel di Yogyakarta, yang selesai pada 1922. Hingga tahun 1939, hampir seluruh Kota Yogyakarta, mulai dari Pingit hingga Wirobrajan, telah teraliri listrik. Selain pemukiman, listrik juga digunakan untuk penerangan jalan umum, yang biayanya ditanggung oleh Keraton Yogyakarta.

Hasil akhir dari analisis ini adalah peta rekomendasi rute walking tour KCB Kotabaru. Peta ini berfungsi sebagai panduan bagi wisatawan yang ingin menjelajahi Kotabaru dengan rute yang efisien. Dengan adanya peta ini, pengunjung dapat dengan mudah menentukan jalur terbaik untuk mengunjungi 16 titik objek cagar budaya yang menjadi ciri khas kawasan Kotabaru.
Kesimpulan
Kotabaru Yogyakarta merupakan kawasan bersejarah yang dibangun pada era kolonial Belanda dengan konsep Garden City, yang kini telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB). Seiring meningkatnya minat terhadap wisata sejarah, analisis rute walking tour berbasis GIS dilakukan untuk menentukan jalur yang optimal dalam menjelajahi Kotabaru. Dengan menggunakan metode network analysis dan isochrone analysis, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam waktu 5 menit berjalan kaki hanya 6 dari 16 titik cagar budaya yang dapat dijangkau, sedangkan dalam waktu 10 menit seluruh titik cagar budaya terjangkau. Analisis jaringan rute menunjukkan bahwa total waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi seluruh titik dengan berjalan kaki adalah sekitar 40 menit tanpa berhenti atau sekitar 120 menit jika setiap titik dikunjungi selama 5 menit. Hasil akhir penelitian ini adalah peta rekomendasi rute walking tour Kotabaru, yang dapat digunakan sebagai panduan bagi wisatawan untuk menikmati kekayaan sejarah dan arsitektur kawasan ini secara lebih efektif dan efisien.
Daftar Pustaka
- Darmosugito. (1956). 200 tahun Yogyakarta, 1756-1956. Pemda Dati I DIY.
- Kristiawan, Y. B. (2013). Konsep Garden City di Kawasan Kotabaru Yogyakarta. Dalam L. P. UAJY (Ed.), Konservasi Arsitektur Kota Yogyakarta. Kanisius.
- Wahyu, H. T. (2011). Pelestarian dan Pemanfaatan Bangunan Indis di Kawasan Kotabaru (Tesis Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada).
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 31 Oktober). Museum TNI AD. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/museum-tni-ad-2/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 22 Agustus). Gereja HKBP. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/gereja-hkbp/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 28 Maret). Gereja St. Antonius Yogyakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/gereja-st-antonius-yogyakarta/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 23 Agustus). Kolese St. Ignatius. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/kolese-st-ignatius/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2015, 30 Januari). Sejarah Masjid Syuhada. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/sejarah-masjid-syuhada/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 27 Maret). Gedung SD Ungaran. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/gedung-sd-ungaran/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2021, 15 Juli). Gedung SMA BOPKRI I Yogyakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/gedung-sma-bopkri-i-yogyakarta/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2022, 9 Februari). Rumah Sakit Petronella (Rumah Sakit Bethesda). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/rumah-sakit-bethesda/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 31 Oktober). Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara (DKT). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/rumah-sakit-dinas-kesehatan-tentara-dkt/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 28 Maret). Kantor Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Yogyakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/kantor-dinas-pariwisata-dan-budaya-kota-yogyakarta/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2018, 2 Februari). Bangunan Gardu ANIEM. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/bangunan-gardu-aniem/
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta. (2019, 31 Oktober). Asrama Kompi Kotabaru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/asrama-kompi-kotabaru/
- Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. (n.d.). Babon Aniem Kotabaru. Pemerintah Kota Yogyakarta. https://kebudayaan.jogjakota.go.id/page/index/babon-aniem-kotabaru
- Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru. (n.d.). Sejarah Gereja. https://parokikotabaru.org/sejarah-gereja/
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). Bangunan Jalan Sajiono Nomor 7. https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/4355/bangunanjalansajiononomor
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). Museum TNI AD. https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/199/museum-tni-ad
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). Kantor Dinas Pariwisata Yogyakarta. https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/1022/kantor-dinas-pariwisata-yogyakarta
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (n.d.). Asrama Kompi Kotabaru. https://jogjacagar.jogjaprov.go.id/detail/407/asrama-kompi-kotabaru


![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)
![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)