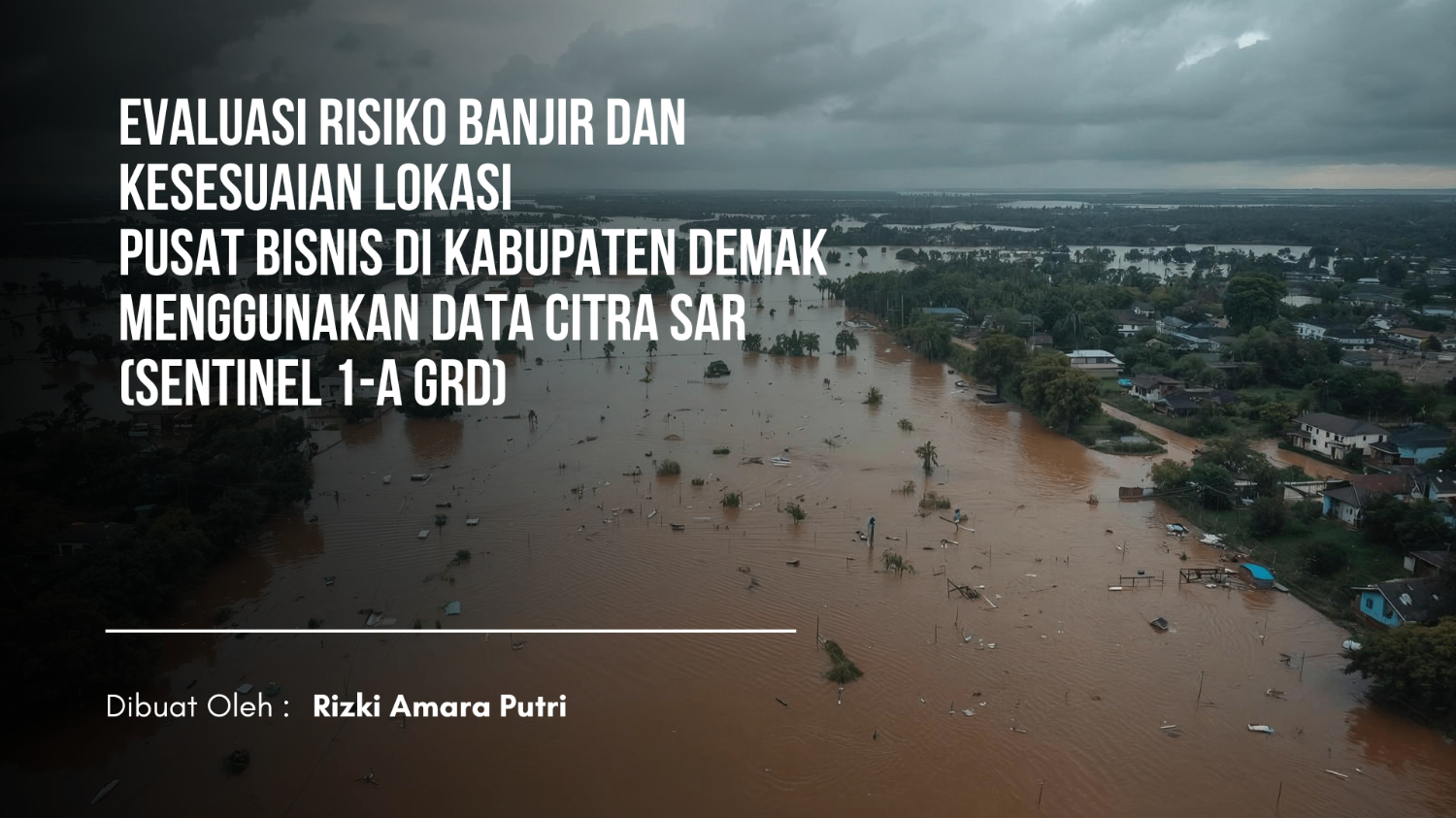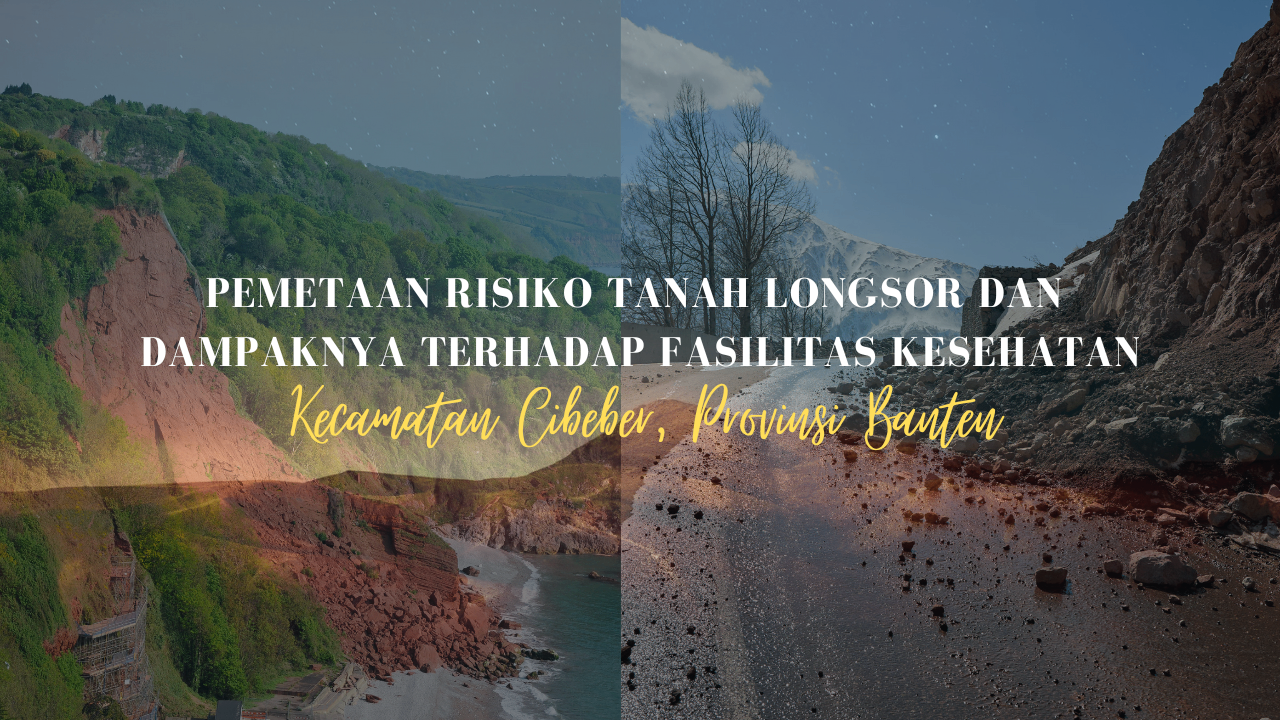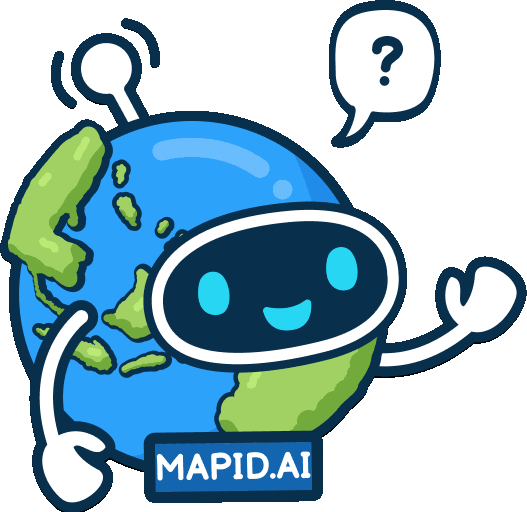Penulis : Raya Nirwanawati dan Cahya Annisa Kamilah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat kerentanan terhadap penyebaran COVID-19 di Desa Candiroto, Kabupaten Temanggung, dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya risiko penyebaran COVID-19 akibat kepadatan penduduk dan interaksi sosial yang tinggi, khususnya di wilayah pusat desa. Meskipun pandemi COVID-19 telah terjadi di masa lampau, dampaknya memberikan pelajaran penting tentang bagaimana karakteristik spasial suatu wilayah dapat mempercepat penyebaran penyakit menular. Dalam penelitian ini, tingkat kerentanan dianalisis berdasarkan empat parameter utama yaitu kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, masing-masing terdiri atas beberapa variabel yang diberi bobot menggunakan metode AHP. Data spasial dan non-spasial kemudian diolah menggunakan metode weighted overlay untuk menghasilkan peta kerentanan dalam tiga klasifikasi yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah persil kerentanan tinggi 463 persil (44%), kerentanan sedang 567 persil (54%), dan kerentanan rendah 18 persil (2%). Zona kerentanan tinggi terkonsentrasi di pusat desa, sementara zona kerentanan rendah berada di bagian pinggiran. Peta kerentanan ini diharapkan menjadi alat bantu penting bagi pemerintah desa dalam menyusun strategi mitigasi dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran. Selain itu, peta ini juga memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta partisipasi aktif dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 secara mandiri dan kolektif.
Kata kunci: COVID-19; Kerentanan spasia; AHP; Weighted overlay; Desa Candiroto; Peta kerentanan
1. PENDAHULUAN
Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 telah menimbulkan dampak luas, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi (WHO, 2020). Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 memang telah berlalu, namun dampaknya masih menyisakan pelajaran penting dalam penanganan wabah di masa depan. Meskipun kasus aktif telah menurun, analisis terhadap penyebaran COVID-19 tetap relevan sebagai referensi dalam membangun sistem kewaspadaan dini dan mitigasi berbasis spasial terhadap penyakit menular lainnya. Di Indonesia, penanganan pandemi memerlukan respons cepat dan tepat, termasuk di tingkat desa yang memiliki karakteristik geografis dan demografis beragam. Desa-desa di wilayah perbukitan maupun dataran rendah menunjukkan pola sebaran kasus yang berbeda, sehingga penting untuk melakukan analisis spasial guna memahami faktor-faktor kerentanan wilayah.
Pemetaan kerentanan merupakan upaya strategis dalam mitigasi pandemi. Peta ini menyajikan gambaran visual mengenai tingkat risiko di tiap wilayah. Dengan dukungan data spasial dan non-spasial, alokasi sumber daya seperti tenaga kesehatan, vaksin, dan sosialisasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Tanpa pemetaan, distribusi tersebut berisiko tidak merata dan kurang tepat sasaran.
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dipilih dalam penelitian ini karena kemampuannya menggabungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif melalui perbandingan berpasangan. AHP juga menghasilkan bobot kepentingan setiap kriteria secara sistematis (Makkasau, 2012). Metode ini banyak digunakan dalam penelitian alokasi bantuan sosial selama pandemi. Namun, penerapannya dalam pemetaan kerentanan COVID-19 secara komprehensif di skala desa masih terbatas. (Ikhsan & Pramono, 2020).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerentanan Desa Candiroto, Kabupaten Temanggung, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Desa Candiroto dipilih karena memiliki karakteristik demografis dan spasial yang kompleks, seperti permukiman padat di pusat desa, aksesibilitas terhadap fasilitas umum yang tinggi, serta keragaman kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menjadikan Desa Candiroto sebagai representasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana berbagai parameter kerentanan berinteraksi dalam konteks wilayah perdesaan. Hasil dari penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk peta kerentanan sebagai alat bantu visual untuk memetakan wilayah-wilayah berisiko, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya mitigasi dan penanganan pandemi di tingkat desa.
2. METODE PENELITIAN
2.1 Lokasi Penelitian
Desa Candiroto merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, desa ini berada di wilayah dataran tinggi dengan kontur wilayah yang sebagian besar berbukit dan bergelombang. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergerak di sektor pertanian. Secara geografis, Desa Candiroto terletak pada koordinat 7°10'48" LS dan 110°3'49" BT.

Gambar 1. Batas Administrasi Desa Candiroto
2.2 Variabel Penelitian
Variabel dalam penelitian kerentanan covid 19 ini terbagi dalam variabel terikat dan variabel bebas.
1. Variabel terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kerentanan terhadap COVID-19.
2. Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi empat parameter utama, yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Parameter kerentanan fisik mencakup dua kriteria utama, yaitu jarak terhadap jalan raya (buffer jalan raya) dan kedekatan dengan fasilitas layanan kesehatan (buffer fasilitas umum kesehatan).
Sementara itu, parameter kerentanan sosial terdiri dari lima kriteria yaitu jumlah penghuni dalam rumah, keberadaan balita, keberadaan lansia, luas lahan atau bangunan (persil), serta tipe atau jenis rumah tinggal.
Parameter kerentanan ekonomi mencakup tiga aspek, yaitu jenis pekerjaan, keberadaan usaha, dan status kepemilikan Kartu Keluarga (KK). Adapun parameter kerentanan lingkungan meliputi empat kriteria yaitu tingkat kebersihan lingkungan RT, keberadaan kelompok PKK, ketersediaan MCK permanen di tiap rumah, dan adanya taman di lingkungan rumah.
2.3. Metode
Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan prioritas dan kriteria tertentu (Bhushan & Rai, 2007). Konsep ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an dan berfungsi sebagai proses untuk menentukan prioritas alternatif melalui perbandingan antar kriteria dalam sebuah struktur hierarki yang bersifat subjektif. Dalam penerapannya, AHP menghasilkan prioritas alternatif menggunakan matriks perbandingan berpasangan dengan skala penilaian subjektif. Metode ini memfasilitasi proses penentuan prioritas alternatif dengan membandingkan kriteria dan sub-kriteria dalam susunan hierarki (Saaty, 1980).
Langkah-langkah utama dalam metode AHP meliputi penyusunan hirarki permasalahan, pembuatan matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison), penghitungan nilai bobot, dan pengujian konsistensi. Bobot yang dihasilkan dari metode ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam analisis spasial untuk menghasilkan peta kerentanan (Purba & Sari, 2021).
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan pelaksanaan penelitian ini, berikut disajikan diagram alir proses penelitian yang memuat alur kerja mulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir, sehingga dapat mempermudah pemahaman terhadap langkah-langkah yang dilakukan selama penelitian.

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian
Proses penyusunan peta kerentanan dalam penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk memperoleh landasan teori dan referensi yang relevan terkait konsep kerentanan serta metode yang digunakan. Setelah itu dilakukan penentuan masalah guna merumuskan fokus kajian yang akan dianalisis. Langkah selanjutnya adalah penentuan bobot masing-masing parameter kerentanan dengan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). Parameter yang digunakan meliputi kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Setelah bobot ditentukan, dilakukan digitasi persil rumah sebagai unit analisis pada peta. Setiap parameter kemudian diberikan skor sesuai tingkat kerentanannya. Hasil dari skoring ini kemudian digabungkan menggunakan metode weighted overlay untuk menghasilkan peta kerentanan secara komposit. Tahap terakhir dari proses ini adalah penyajian peta kerentanan sebagai output akhir yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut maupun pengambilan keputusan.
2.4 Bobot Parameter
Masing-masing parameter kerentanan memiliki variabel yang berbeda. Dalam parameter kerentanan fisik terdiri dari 2 variabel yaitu buffer jalan raya dan buffer fasilitas umum Kesehatan. Parameter kerentanan sosial terdapat 5 variabel yaitu jumlah penghuni, penghuni balitas, penghuni manula, luas persil, dan jenis rumah. Parameter ekonomi terdiri dari 3 variabel yaitu pekerjaan, usaha, dan status KK. Parameter lingkungan terdiri dari 3 variabel yaitu kebersihan lingkungan RT, unit PKK, MCK permanen per rumah, dan taman per rumah. Berikut ini merupakan bobot untuk masing-masing kriteria yang telah dihitung menggunakan metode AHP.

Setelah dilakukan perhitungan bobot untuk masing-masing kriteria, tahapan selanjutnya yaitu melakukan overlay dengan menggunakan weighted overlay pada masing-masing kriteria kerentanan sehingga akan didapatkan 4 layer untuk menentukan peta kerentanan COVID-19. Layer tersebut di antaranya adalah layer kerentanan fisik, kerentanan lingkungan, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Untuk mendapatkan peta kerentanan COVID-19 diperlukan proses overlay dari masing-masing kerentanan sehingga diperlukan perhitungan AHP dari ke-empat parameter kerentanan tersebut. Adapun berikut ini merupakan bobot untuk setiap parameter yang telah dihitung menggunakan metode AHP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kerentanan Fisik COVID-19
Kerentanan fisik dianalisis berdasarkan dua kriteria, yaitu jarak terhadap jalan raya dan jarak ke fasilitas umum kesehatan (fasum). Rumah yang terletak sangat dekat dengan jalan raya (sekitar 100 meter) dianggap memiliki tingkat kerentanan tinggi karena lebih mudah terpapar keramaian, polusi, dan potensi penyebaran penyakit, sehingga diberi skor tinggi. Sebaliknya, rumah yang berjarak lebih dari 250 meter dari jalan raya mendapat skor rendah. Pada aspek buffer fasum kesehatan, rumah yang berlokasi dekat (kurang dari 500 meter) dengan fasilitas kesehatan dianggap lebih aman dan mendapat skor rendah, sedangkan rumah yang jauh (lebih dari 1 km) dari fasilitas tersebut diberi skor tinggi karena keterbatasan akses layanan kesehatan dalam kondisi darurat.
3.2 Kerentanan Sosial COVID-19
Kerentanan sosial dinilai melalui lima variabel, yaitu jumlah penghuni rumah, keberadaan balita dan manula, luas persil, serta jenis rumah. Semakin banyak jumlah penghuni dalam satu rumah, terutama jika lebih dari lima jiwa, maka skor kerentanan akan semakin tinggi karena potensi penularan penyakit meningkat dalam hunian padat. Keberadaan penghuni balita dan manula juga meningkatkan kerentanan karena kedua kelompok ini termasuk rentan terhadap paparan penyakit, sehingga diberi skor lebih tinggi. Luas persil turut berpengaruh, di mana rumah dengan luas di bawah 60 m² mendapat skor tertinggi karena keterbatasan ruang dapat memperburuk kondisi kesehatan dan kenyamanan penghuni. Jenis rumah juga menjadi indikator penting, rumah non permanen diberikan skor tertinggi karena cenderung kurang kokoh dan memiliki kualitas sanitasi atau ventilasi yang kurang baik, sedangkan rumah permanen diberi skor rendah sebagai indikator kerentanan yang lebih kecil.
3.3 Kerentanan Ekonomi COVID-19
Kerentanan ekonomi dalam penelitian ini ditentukan oleh tiga variabel, yaitu pekerjaan kepala keluarga (KK), keberadaan usaha KK, dan status ekonomi KK. Pekerjaan KK dengan pendapatan tetap seperti PNS diberi skor rendah karena dianggap memiliki ketahanan ekonomi yang baik, sedangkan pekerjaan seperti sopir, pedagang, dan serabutan mendapat skor tinggi karena berisiko secara ekonomi. Keberadaan usaha juga mempengaruhi kerentanan. KK yang memiliki usaha memperoleh skor lebih tinggi dibanding yang tidak memiliki usaha, karena meskipun berpotensi menambah penghasilan, usaha tidak selalu menjamin kestabilan ekonomi. Status KK diklasifikasikan menjadi mampu, sedang, dan tidak mampu, di mana kategori tidak mampu memperoleh skor tertinggi sebagai indikator kerentanan ekonomi yang tinggi.
3.4 Kerentanan Lingkungan COVID-19
Kerentanan lingkungan dinilai berdasarkan kebersihan lingkungan RT, keaktifan unit PKK, ketersediaan MCK permanen per rumah, dan keberadaan taman. Lingkungan yang bersih, adanya unit PKK yang aktif, MCK permanen, serta taman yang baik menunjukkan tingkat kerentanan lingkungan yang rendah, karena mencerminkan dukungan sosial dan kualitas hidup yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang kotor, unit PKK yang tidak aktif, tidak adanya MCK permanen, dan ketiadaan taman menunjukkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap risiko kesehatan dan penyebaran penyakit seperti COVID-19.
3.5 Hasil dan Pembahasan Peta Kerentanan COVID-19
Peta Kerentanan COVID-19 adalah representasi spasial yang menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap risiko penyebaran COVID-19. Peta ini disusun berdasarkan analisis berbagai faktor yang memengaruhi tingkat risiko di suatu daerah, seperti kondisi fisik lingkungan, faktor sosial, kondisi ekonomi masyarakat, serta faktor lingkungan pendukung lainnya yang digabungkan menggunakan metode weighted overlay dengan bobot yang telah ditentukan menggunakan metode AHP sebelumnya.

Gambar 3. Peta Kerentanan
Secara visual, peta kerentanan COVID-19 Desa Candiroto menunjukkan distribusi tingkat kerentanan dalam tiga kelas, yaitu rendah (hijau), sedang (kuning), dan tinggi (merah). Area dengan warna merah mendominasi wilayah permukiman padat, terutama di bagian tengah desa yang berdekatan dengan jalur utama dan fasilitas umum, menunjukkan tingkat kerentanan paling tinggi. Warna kuning tersebar di sekitar zona merah sebagai wilayah transisi, sedangkan warna hijau berada di pinggiran desa dengan kepadatan rendah dan akses terbatas ke pusat aktivitas.
Hasil dari proses analisis menggunakan metode weighted overlay menghasilkan peta kerentanan COVID-19 yang terbagi ke dalam tiga kelas. Klasifikasi ini diperoleh berdasarkan skor akhir dari penggabungan seluruh parameter kerentanan, dengan mempertimbangkan bobot yang telah ditentukan sebelumnya melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP).
Secara kuantitatif, jumlah seluruh persil di Desa Candiroto berjumlah 1048 persil yang termasuk dalam masing-masing kelas kerentanan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kelas Rendah
Kelas ini merepresentasikan wilayah dengan tingkat kerentanan paling kecil terhadap penyebaran COVID-19 dengan total 18 persil atau 2% dari total keseluruhan persil. Umumnya berada di area dengan kepadatan penduduk rendah, akses terbatas terhadap fasilitas umum, serta aktivitas sosial masyarakat yang tidak terlalu tinggi. Total luasan yang berada dalam kelas rendah adalah 2.783 m2.
2. Kelas Sedang
Wilayah dengan kerentanan sedang merupakan zona transisi antara kelas rendah dan tinggi dengan total persil 567 persil atau 54% dari total keseluruhan persil. Karakteristik wilayah ini memiliki kepadatan permukiman yang cukup dengan tingkat aktivitas masyarakat yang moderat. Risiko penyebaran COVID-19 masih ada, namun tidak sebesar di zona tinggi. Total luasan yang berada dalam kelas sedang adalah 95.208 m2.
3. Kelas Tinggi
Zona kerentanan tinggi berjumlah 463 persil atau 44% dari total keseluruhan persil. Zona ini didominasi oleh area dengan kepadatan penduduk yang tinggi, akses mudah ke fasilitas umum seperti pasar, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat aktivitas masyarakat lainnya. Intensitas interaksi sosial yang tinggi di kawasan ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya tingkat kerentanan terhadap penyebaran COVID-19. Total luasan yang berada dalam kelas sedang adalah 74.258 m2.
Secara spasial, distribusi kelas kerentanan menunjukkan pola konsentris, di mana wilayah dengan kerentanan tinggi terpusat di bagian tengah desa, diikuti oleh zona kerentanan sedang sebagai penyangga, dan kelas rendah tersebar di area pinggiran. Pemetaan kerentanan ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan berbasis risiko. Tanpa adanya pemetaan kerentanan, zona berisiko tinggi seperti area pusat desa yang padat dapat menjadi hotspot penyebaran penyakit yang tidak terkendali, memicu lonjakan kasus, membebani fasilitas kesehatan, serta meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Penyebaran virus pun dapat meluas dari pusat ke pinggiran desa, menciptakan gelombang infeksi yang berulang. Selain itu, ketiadaan peta kerentanan menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien, karena distribusi bantuan, vaksinasi, dan edukasi dilakukan secara seragam tanpa prioritas pada area paling rentan. Hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan di wilayah berisiko rendah, sementara wilayah yang sangat membutuhkan justru kekurangan intervensi. Kurangnya peta juga berdampak pada rendahnya kewaspadaan masyarakat karena mereka tidak memiliki gambaran risiko di lingkungan masing-masing. Akibatnya, muncul sikap lengah di zona tinggi atau justru kepanikan berlebihan di zona rendah, sehingga partisipasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan menjadi tidak optimal. Lebih jauh, ketiadaan peta kerentanan mempersulit pemerintah desa dalam menyusun kebijakan mitigasi berbasis data, menjadikan keputusan yang diambil bersifat reaktif dan kurang terarah. Dampaknya, upaya penanganan menjadi tidak efektif dan memperpanjang krisis kesehatan serta ekonomi di tingkat lokal.
3.6 Analisis Spasial Peta Kerentanan
Peta kerentanan COVID-19 yang telah disusun memperlihatkan distribusi spasial tingkat kerentanan di wilayah Desa Candiroto. Secara spasial, zona kerentanan tinggi (warna merah) mendominasi bagian tengah desa, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang terletak di sepanjang jalur utama dan di sekitar fasilitas umum. Wilayah ini merupakan pusat aktivitas masyarakat, sehingga interaksi antarpenduduk relatif lebih intens. Selain itu, keberadaan fasilitas umum seperti pasar dan fasilitas kesehatan juga berkontribusi terhadap tingginya potensi kerentanan akibat tingginya mobilitas masyarakat di area tersebut. Tingkat kepadatan hunian yang tinggi mempersempit ruang gerak individu, sehingga protokol kesehatan seperti jaga jarak lebih sulit diterapkan. Pola distribusi ini mengkonfirmasi relevansi parameter-parameter seperti kepadatan fisik, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, serta intensitas interaksi sosial yang telah dianalisis dan diberi bobot melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP), sehingga menghasilkan representasi kerentanan yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sementara itu, zona kerentanan sedang (warna kuning) tersebar di sekitar zona tinggi dan berfungsi sebagai area transisi. Wilayah ini masih memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, namun dengan kepadatan permukiman yang sedikit lebih rendah dibandingkan zona merah. Interaksi sosial tetap ada, namun tidak seintens di zona pusat. Sedangkan zona kerentanan rendah (warna hijau) umumnya berada di bagian pinggir desa. Area ini merupakan kawasan dengan kepadatan permukiman rendah, akses terbatas ke fasilitas umum, serta aktivitas sosial masyarakat yang cenderung lebih sedikit. Secara umum, risiko penyebaran COVID-19 di zona ini relatif lebih kecil dibandingkan zona lainnya.
3.7 Manfaat Bagi Masyarakat
Peta kerentanan COVID-19 memiliki peranan penting bagi masyarakat sebagai media informasi spasial mengenai tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayah tempat tinggal mereka. Dengan adanya peta ini, masyarakat dapat memahami kondisi lingkungannya secara lebih jelas, terutama terkait wilayah-wilayah yang termasuk dalam kategori kerentanan tinggi, sedang, maupun rendah. Sesuai dengan hasil pemetaan didapatkan jumlah persil kerentanan tinggi 463 persil (44%), kerentanan sedang 567 persil (54%), dan kerentanan rendah 18 persil (2%).
Informasi spasial yang dihasilkan dari pemetaan kerentanan COVID-19 ini merefleksikan hasil pengolahan data berbasis metode Analytical Hierarchy Process (AHP), di mana setiap parameter seperti kepadatan penduduk, akses terhadap fasilitas kesehatan, jenis pekerjaan, dan kondisi lingkungan telah diberi bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap risiko penyebaran. Bagi pemerintah desa, peta ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi intervensi yang lebih terukur, seperti penempatan fasilitas kesehatan sementara di zona merah, pengalokasian anggaran untuk edukasi intensif di wilayah berisiko tinggi, serta penyaluran bantuan sosial berdasarkan tingkat kebutuhan yang objektif. Sementara itu, bagi masyarakat, informasi kerentanan ini berfungsi meningkatkan kesadaran berbasis lokasi dan mendorong kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi lingkungannya.
Tanpa pemetaan kerentanan COVID-19, penyebaran virus berisiko tidak terkendali karena wilayah dengan risiko tinggi tidak teridentifikasi secara jelas. Hal ini mempersulit upaya mitigasi dan memungkinkan lonjakan kasus dari pusat aktivitas ke area sekitar. Alokasi sumber daya seperti bantuan, vaksin, dan edukasi juga menjadi tidak efisien karena tidak berbasis prioritas risiko. Selain itu, masyarakat kehilangan acuan dalam menilai tingkat bahaya di lingkungan mereka, yang berdampak pada rendahnya kedisiplinan dan partisipasi. Pemerintah desa pun kesulitan mengambil keputusan strategis karena tidak memiliki data spasial yang mendukung, sehingga intervensi cenderung reaktif dan kurang tepat sasaran.
4. KESIMPULAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kerentanan Desa Candiroto terhadap pandemi COVID-19 terbagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jumlah persil kerentanan tinggi 463 persil (44%), kerentanan sedang 567 persil (54%), dan kerentanan rendah 18 persil (2%). Wilayah dengan kerentanan tinggi umumnya berada di pusat desa dengan kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat yang tinggi, sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah berada di bagian pinggir desa. Peta kerentanan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam menentukan prioritas upaya mitigasi dan pencegahan penyebaran COVID-19 secara lebih tepat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Bhushan, N. & Rai, K., 2007. Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process. Springer Science & Business Media.
Ikhsan, F. K. & Pramono, D. E. H., 2020. SPK menggunakan metode AHP untuk pemberlakuan lockdown di kecamatan yang terdampak Covid‑19 di Kota Bandar Lampung. EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi.
Makkasau, K., 2012. Penggunaan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dalam penentuan prioritas program kesehatan (Studi kasus program promosi kesehatan). Jati Undip: Jurnal Teknik Industri..
Purba, D. H. & Sari, E. P., 2021. Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam Penentuan Prioritas Penanganan Bencana. Jurnal Geografi, 13(2), pp. 123-133.
Saaty, T. L., 1980. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting. McGraw‑Hill: Resource Allocation.
WHO, 2020. Impact of COVID‑19 on people’s livelihoods, their health and our food systems., s.l.: Joint statement by ILO, FAO, IFAD, and WHO. .


![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)
![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)

![[GEODATA] Point of Interest (POI)](https://mapidstorage.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/foto_doc/mapidseeit/doc_1648452337_d8074cde-5aef-4820-88ba-b6cc500a7e04.jpeg)