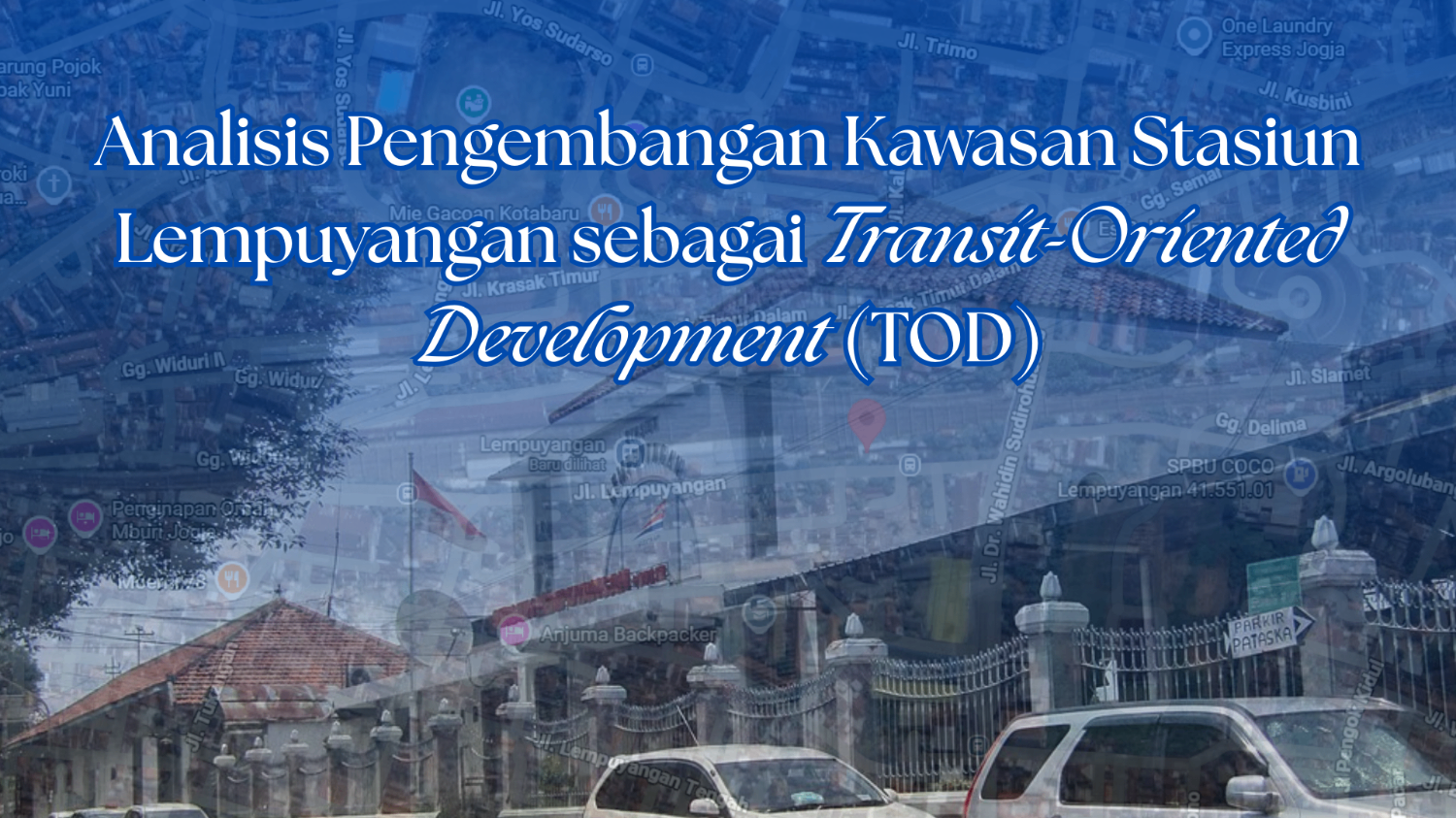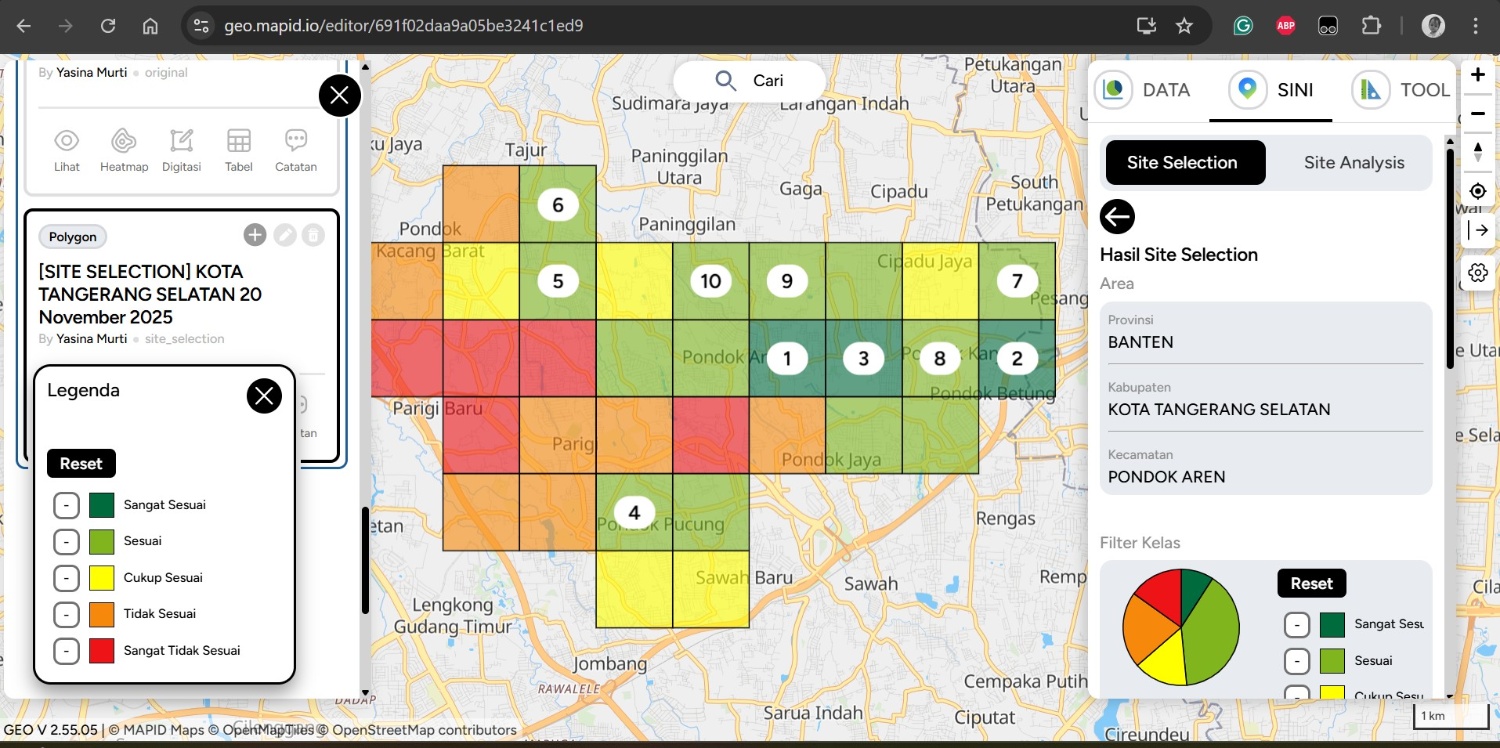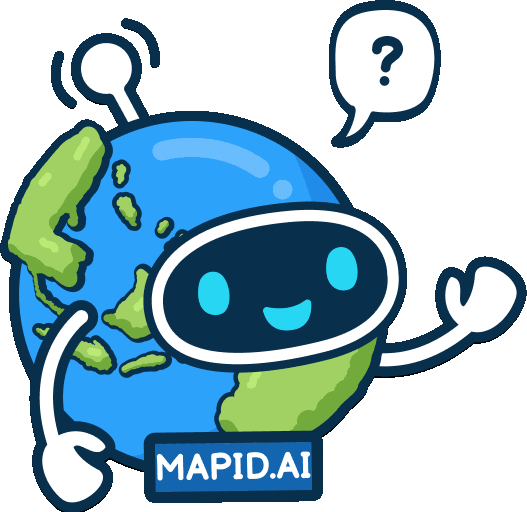Latar Belakang
Secara geografis, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo Australia. Letak geografis ini yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Secara umum, kejadian longsor dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Potensi terjadinya pergerakan lereng tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusunannya, struktur geologi, curah hujan, dan penggunaan lahan.
Bencana tanah longsor sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana tanah longsor menempati posisi ketiga dalam urutan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dengan total 634 kejadian selama tahun 2022. Hal ini membuktikan bahwa bencana tanah longsor di Jawa Barat sudah menjadi masalah yang besar. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk pencegahan atau pengurangan risiko akibat terjadinya bencana tersebut. Penentuan tingkat risiko dilakukan oleh BNPB. BNPB menerbitkan Indeks Risiko Bencana Indonesia pada tahun 2013. Indeks risiko terdiri dari komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam mengatasi bencana. Penurunan risiko dapat diturunkan dengan menurunkan kerentanan dari bencana tersebut (BNPB 2021). Oleh karena itu, proyek ini akan melakukan kajian lebih lanjut untuk melakukan analisis spasial terhadap kerentanan bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kota Cimahi.
Tujuan
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mendapatkan Peta Kerentanan Tanah Longsor di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu dalam satuan kecamatan.
Tinjauan Pustaka
Menurut Rosita dkk. (2018), tanah longsor adalah gerakan massa tanah atau batuan yang bergerak turun dan keluar lereng karena kestabilan tanah yang terganggu yang disebabkan oleh faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng dan faktor pemicu. Tanah longsor terjadi akibat adanya keruntuhan geser di sepanjang bidang longsor yang merupakan batas bergeraknya massa tanah atau batuan (Hardiyatmo, 2012: 1). Kondisi geologi yang kompleks dengan gerakan tektonik yang multi periodik serta erosi yang tinggi dan dipicu oleh curah hujan akan menyebabkan peningkatan risiko longsor (Wen dkk., 2017). Terdapat beberapa faktor penyebab bencana tanah longsor, yaitu faktor geologi, morfologi, fisik, dan manusia (Muntohar, 2010).
Goenadi (2003) mengelompokkan faktor pemicu bencana tanah longsor atas dua bagian, yaitu faktor statis dan faktor dinamis. Yang tergolong dalam faktor dinamis pemicu bencana tanah longsor adalah curah hujan dan penggunaan lahan. Untuk kasus bencana tanah longsor yang terjadi di Indonesia, sebagian besar diakibatkan oleh faktor dinamis, yaitu kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi ataupun durasi hujan yang lama, keadaan topografi lereng yang curam, dan tingginya populasi penduduk di daerah berlereng atau perbukitan.
Data
Tabel 1: Data

Tahapan Penelitian

Gambar 1: Alur penelitian
Hasil
Penelitian ini menggunakan 16 jenis data dan dibagi menjadi 4 parameter sebagai parameter utama, yaitu kerentanan fisik, kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan lingkungan. Nilai kerentanan sosial didapatkan dengan melakukan pengolahan data menggunakan skoring dan pembobotan dari data kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio umur rentan, rasio penyandang disabilitas dan rasio penduduk miskin. Nilai kerentanan ekonomi didapatkan dengan melakukan pengolahan data menggunakan skoring dan pembobotan dari nilai PDRB dan luas lahan produktif. Nilai kerentanan fisik didapatkan dengan melakukan pengolahan data menggunakan skoring dan pembobotan dari data jumlah rumah, jumlah fasilitas umum, dan jumlah fasilitas kritis. Nilai kerentanan lingkungan didapatkan dengan melakukan pengolahan data menggunakan skoring dan pembobotan dari data luas hutan. Di bawah ini merupakan hasil dan skor untuk setiap kelas pada semua parameter yang digunakan.
1. Kerentanan Fisik

Gambar 2: Peta kerentanan fisik
Tabel 2: Bobot dan kelas parameter fisik

2. Kerentanan Sosial

Gambar 3: Peta kerentanan sosial
Tabel 3: Bobot dan kelas parameter sosial

3. Kerentanan Ekonomi

Gambar 4: Peta kerentanan ekonomi
Tabel 4: Bobot dan kelas kerentanan ekonomi

4. Kerentanan Lingkungan

Gambar 5: Peta kerentanan lingkungan
Tabel 5: Bobot dan kelas kerentanan lingkungan

Setelah semua parameter diberi skor, giliran keempat parameter yang digunakan diberi bobot untuk dilakukan pengolahan kerentanan tanah longsor.

Gambar 6: Peta kerentanan tanah longsor
Tabel 6: Bobot dan kelas kerentanan tanah longsor

Hasil pengolahan menunjukkan peta tingkat kerentanan tanah longsor. Tingkatan kerentanan tanah longsor dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Analisis
Setiap parameter pada setiap jenis kerentanan dilakukan pengolahan dengan bobot masing-masing yang dilakukan join table ke dalam data vektor batas administrasi setiap kecamatan pada wilayah studi. Setiap kerentanan memiliki tiga kelas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. hasil nilai setiap kerentanan dilakukan perhitungan kembali untuk mendapatkan nilai kerentanan bencana tanah longsor di wilayah studi. Secara keseluruhan, tingkat kerentanan bencana tanah longsor di daerah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu tersebar ke dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi.
Kerentanan sosial terdiri dari lima faktor penentu, yaitu kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat, dan rasio kelompok umur. Berdasarkan lima faktor tersebut, faktor kepadatan penduduk sangat mempengaruhi nilai dari kerentanan sosial dikarenakan kepadatan penduduk memiliki bobot 60%. Semakin padatnya jumlah penduduk yang ada di suatu wilayah, maka kerentanannya terhadap bencana tanah longsor semakin tinggi. Risiko korban jiwa pada kejadian longsor di suatu wilayah dengan penduduk yang padat akan semakin tinggi.
Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerentanan ekonomi dalam penelitian ini terdiri dari faktor lahan produktif dan PDRB daerah. Lahan produktif sangat mempengaruhi nilai kerentanan ekonomi dikarenakan lahan produktif memiliki bobot 60%. Lahan produktif mempunyai kerentanan yang tinggi jika dibandingkan dengan lahan tidak produktif. Ketika terjadinya bencana tanah longsor, maka kerugian ekonomi yang dialami lebih tinggi jika dibandingkan dengan lahan yang tidak produktif .
Faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan fisik, yaitu jumlah rumah, jumlah fasilitas umum, dan jumlah fasilitas kritis di daerah tersebut. Jumlah rumah sangat mempengaruhi kerentanan fisik dengan bobot 40%. Semakin banyak rumah yang terkena bencana, maka semakin tinggi risiko kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat dikarenakan harga jual rumah yang cukup tinggi bagi masyarakat.
Kerentanan lingkungan dipengaruhi oleh luas hutan. Semakin luas hutan di suatu wilayah, maka semakin besar risiko kerugian yang akan didapatkan dari daerah tersebut jika dibandingkan dengan daerah yang tidak tertutupi oleh hutan. Ini disebabkan oleh hutan yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di suatu daerah.
Dari kelima kerentanan diatas, kerentanan sosial memiliki dampak yang paling tinggi terhadap kerentanan tanah longsor dengan bobot 40% hal ini dikarenakan kerentanan sosial berpengaruh terhadap masyarakat yang ada di daerah tersebut. Semakin tinggi kerentanan sosial di sebuah daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut jika terkena bencana tanah longsor dikarenakan masyarakat merupakan faktor yang dapat membantu mengembangkan atau memperbaiki daerah ketika terjadinya kejadian tanah longsor.
Di daerah penelitian, terdapat salah satu wilayah yang baru saja mengalami bencana longsor, yaitu Kabupaten Cianjur, tepatnya di Kecamatan Cugenang. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperoleh informasi bahwa telah terjadi longsor akibat gempa di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 21 November 2022. Hal ini membuktikan bahwa adanya kerentanan di daerah tersebut sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan kerugian yang akan diterima akibat dari bencana tanah longsor.
Kesimpulan
Peta Kerentanan Tanah Longsor di wilayah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu sudah dihasilkan. Peta ini dibuat dalam satuan kecamatan agar masyarakat mendapatkan informasi lebih teliti untuk digunakan sebagai acuan penentu kebijakan dalam perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan risiko longsor sesuai dengan kondisi wilayah setempat
Daftar Pustaka
Geonadi (2003) Konservasi Lahan Terpadu Daerah Rawan Bencana Longsoran Di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Muntohar. 2010. Tanah longsor. Analisis, Prediksi, Mitigasi
BNPB. 2016. Risiko Bencana Indonesia
Hardiyatmo H C. 2012 Tanah Longsor & Erosi: Kejadian dan Penanganan
Wen dkk (2017) Landslide Susceptibility Assessment Using The Certainty Factor And Analytic Hierarchy Process
Rosita dkk 2018. Daerah Rawan Bencana Geologi Gerakan Tanah Dalam arahan Kebijakan Mitigasi kabupaten Ciamis
BNPB. 2021. Indeks Risiko Bencana Indonesia


![[GEODATA] Tutupan Lahan Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1684312961161_COVER%20GEODATA_%20Tutupan%20Lahan.png)
![[GEODATA] Status Ekonomi dan Sosial (SES) Indonesia](https://mapidstorage.s3.amazonaws.com/general_image/mapidseeit/1693454652933_20230831-085941.jpg.jpeg)

![[GEODATA] Point of Interest (POI)](https://mapidstorage.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/foto_doc/mapidseeit/doc_1648452337_d8074cde-5aef-4820-88ba-b6cc500a7e04.jpeg)